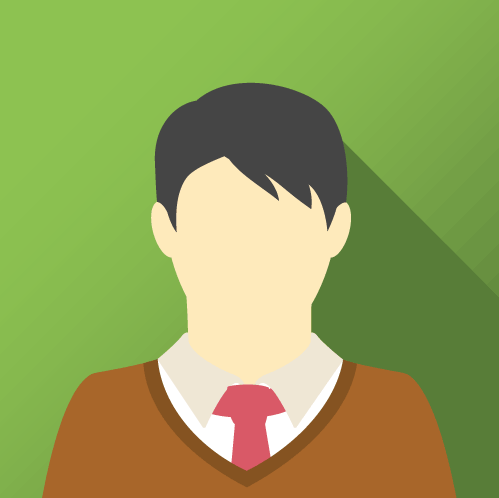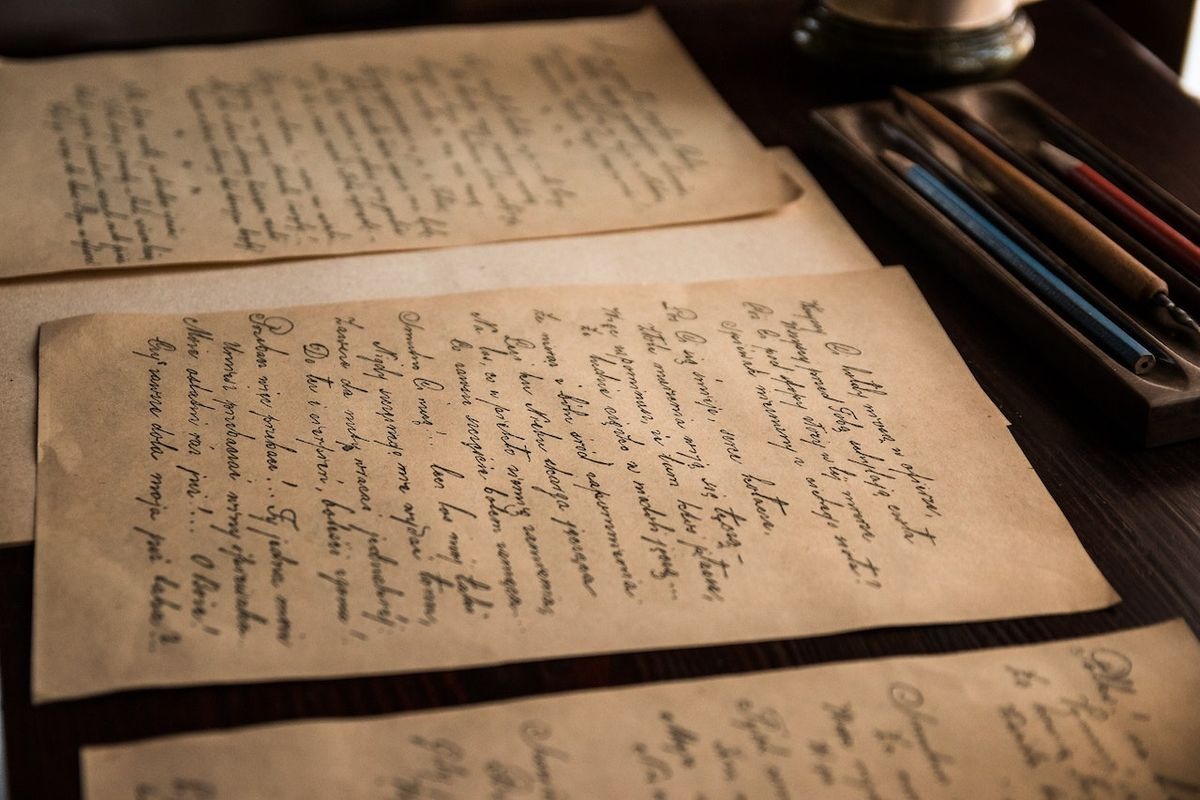ADA pernyataan menarik yang pernah dilontarkan mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha sekitar dua tahun lalu, yang mengatakan bahwa dirinya menemui fakta di lapangan selama proses pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak berlangsung, sejumlah mahar harus diberikan dari calon ke partai. Satu kursi kononnya dinilai seharga 1 miliar. Malah ada lima kursi harus bayar Rp 15 Miliar.
Menurut Putu, fenomena calon kepala daerah memberi mahar kepada partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Saat dirinya menjadi Komisioner KPU, Putu juga pernah mengetahui praktik money politics tersebut. "Dulu itu, satu kursi hanya Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Sekarang lebih mahal lagi. Lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Departemen Riset PARA Syndicate, Toto Sugiarto menilai mahar politik dalam pelaksanaan pilkada hanyalah penomena 'gunung es' yang sulit untuk dihapuskan. Menurutnya, banyak figur yang ingin maju sebagai calon kepala daerah tetap menyanggupi memberikan mahar kepada partai politik sebagai syarat diusulkan mengikuti pilkada.
Macam-macam saja istilah yang digunakan dalam dunia politik hari ini. Biasanya mahar dimaknai berupa pemberian calon suami kepada calon isterinya atau dalam dunia klenik (perdukunan) merupakan “syarat” yang harus dipenuhi dalam transaksi gaib (mistik).
Apapun istilahnya, pemberian mahar politik ini menggambarkan betapa transaksionalnya praktek politik kita sehingga seorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah harus menyiapkan uang ratusan bahkan milyaran rupiah untuk “membeli” kendaraan politiknya. Tentu saja dalam hal ini, calon yang berduit banyak saja yang bisa melakukannya. Itu baru mahar politik, belum lagi biaya sosialisasi dan kampanye pemilu dalam rangka pemenangan calon kepala daerah.
Tak bisa dibayangkan betapa mahalnya biaya politik (political costs) dalam Pilkada di negeri ini. Tentu saja dalam hal ini, calon yang “beruang” banyak sajalah yang bisa bertarung dalam perhelatan demokrasi lokal ini. Sebaliknya calon yang miskin (tak berduit) lebih baik mengurungkan niatnya dan mundur secara teratur.
Kalau seperti inilah praktek politik kita, apakah kita bisa melahirkan kepala daerah yang baik dan bersih?! pada proses awal saja untuk mendapatkan “perahu politik” sudah harus mengorek kantong milyaran rupiah. Belum lagi pada proses-proses selanjutnya. Ya kalau calon kepala daerahnya memang orang kaya tentu saja uang milik pribadi yang dikeluarkan. Kalau tidak, tentu saja akan mencari sponsor (donatur) untuk membiayainya yang pada perkembangannya kemudian akan menjadi “hutang budi politik”.
Dari sinilah asal muasal terbentuknya mentalitas dan prilaku korupsi di kalangan pemimpin kita. Di saat proses pemilihan, mereka sudah menghabiskan uang yang tidak sedikit. Tentu saja setelah menjabat, mereka akan berpikir keras bagaimana “menggantinya”. Akhirnya mereka akan melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Jalan pintas yang paling cepat adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan beragam modus.
Kalau seperti inilah nanti wajah pemimpin kita, maka yang menjadi korban adalah kita (rakyat). Seharusnya berkah otonomi daerah yang membuat uang banyak mengalir ke daerah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat banyak. Tapi jangan sampai kenyataannya yang terjadi nanti malah sebaliknya. Karena itu, kita (rakyat) harus berhati-hati dalam memilih calon kepala daerahnya. Kalau salah memilih pemimpin, maka lima tahun akan menanggung akibatnya. Oleh sebab itu, kita (rakyat) jangan sampai Seperti Memilih Kucing dalam Karung. Mari sukseskan Pilgubri Riau 2018 Wallah A’lam***